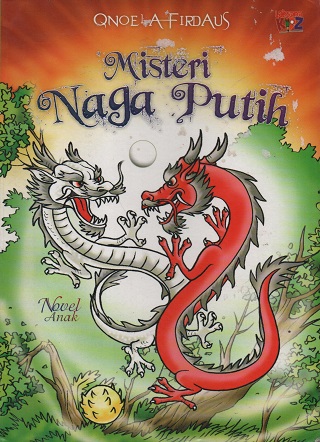Prahara Kanisius: Sebuah 'Noda' Demokrasi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
virus ini juga sering menyerang para pejabat yang pensiun, atlit terkenal yang kalah bertanding, artis yang sudah tidak laku di pasaran.
Tony Rosyid
Di dalam psikoanbalisis ada penyakit namanya "prolonged infantilism" yaitu masa kanak-kanak yang kelamaan. Virus ini dapat dikenali pada diri seseorang atau sekelompok orang yang sulit move on. Contoh misalnya, orang yang dari kecil hidup di keluarga kaya, lalu setelah menikah ia miskin. Jika ia tetap berpola hidup seperti layaknya orang banyak uang, suka makan di restoran dan jalan-jalan ke tempat yang mahal, maka ia telah terjangkit virus "prolonged infantilism." Orang ini susah beradaptasi terhadap realitas yang dihadapi
Tidak saja kepada orang kaya yang jatuh miskin, virus ini juga sering menyerang para pejabat yang pensiun, atlit terkenal yang kalah bertanding, artis yang sudah tidak laku di pasaran. Banyak diantara mereka yang tidak mampu beradapatasi dan menerima realitas perubahan hidupnya. Pasalnya, mereka tidak pernah mengantisipasi dan punya kesiapan menghadapi suatu perubahan. Everest Hagen menyebut orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang berkepribadian otoriter. Orang-orang yang berkepribadian otoriter umumnya tidak bisa menerima nilai-nilai baru dan keadaan yang berbeda dari apa yang dibayangkan oleh otak di kepalanya. Orang-orang macam ini oleh agama (Islam red) disebut "jahiliyah".
Dalam politik, penyakit ini sering juga menular kepada mereka yang kalah dalam kompetisi demokratis. Sejumlah kegaduhan pasca pilpres, pilkada dan pileg akibat tidak bisa menerima hasil pemilu adalah indikator virus "prolonged infaltilism" telah merasuk ke otak mereka. Klinik konstitusional sebagai saluran hukum yang tersedia di MK (Mahkamah Konstitusi) seringkali tidak mampu meyembuhkan penyakit ini.
Keributan di Kemendagri oleh sekelompok orang yang tidak bisa terima hasil pilkada beberapa waktu lalu adalah salah satu contoh masih terus adanya masyarakat terjangkit virus "prolonged infantilism". Orang-orang seperti ini hampir selalu ada dan kemunculannya semakin banyak sejak pemilu digelar secara langsung. Mereka mengaku bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari proses demokrasi. Mungkin mereka menganggap bahwa demokrasi adalah sarana kebebasan tanpa batas. Ini tentu salah kaprah. Mereka lalai bahwa demokrasi bukan "sarana bebas menghujat dan merusak" tapi demokrasi adalah "ruang legal untuk berpendapat". Demokrasi tidak menyediakan sarana menghalalkan semua cara untuk mengejar tujuan.
Banyak orang yang suka klaim dirinya sebagai penganut demokrasi sejati, tapi sikap dan prilakunya jauh dari nilai-nilai yang menunjukkan seorang yang menghormati demokrasi. Apa yang mereka katakan sebagai pejuang demokrasi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang "double talk", ucapan dan sikapnya saling bertentangan. "What they say" berbeda dengan "what they do."
Peristiwa yang sedang ramai dibicarakan publik di media dan medsos akhir-akhir ini terkait aksi walk out sejumlah orang yang dinisiasi oleh Ananda Sukarlan di acara ultah ke 90 Lembaga Pendidikan Kolese Kanisius juga merupakan "ironi demokrasi". Kemarahan terkait keabsahan Anies Baswedan sebagai gubernur mestinya sudah selesai setelah pelantikan. Aturan pilkada yang mesti jadi acuan, bukan perasaan kecewa dan marah karena kekalahan. Aksi Ananda Sukarlan dan kawan-kawan salah waktu dan tempat. Mestinya dilakukan sebelum penetapan KPUD dan di MK.
Secara sosial aksi tersebut sungguh menunjukkan sikap jauh dari etika pendidikan, politik dan kebangsaan . Apalagi dilakukan di lembaga pendidikan sebesar Kanisius dan kepada tamu yang diundang secara resmi oleh pihak sekolah. Perlakuan secara tidak hormat ini merupakan tindakan anti toleransi dan kontra-demokrasi. Apakah ini yang disebut sesuai dengan nilai-nilai Kanisius? Pasti tidak! Sekolah adalah tempat orang-orang beradab, bukan panggung kemarahan orang-orang yang sulit beranjak dewasa. Sebaliknya, sikap Ananda Sukarlan justru merupakan bentuk "kekerasaan budaya" kata Eros Djarot.
Aksi walk out saat Anies berpidato setidaknya telah menodai nama besar Kanisius yang selama ini telah berhasil melahirkan orang-orang sukses dan tokoh-tokoh bangsa. Tindakan ini juga telah mempermalukan para alumninya. Peristiwa ini tidak perlu terjadi jika mereka bisa berlapang dada untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari "historical necessities", keniscayaan sejarah. Dalam sistem demokrasi menang-kalah itu hal biasa dan wajar. Menjadi tidak wajar jika pihak yang kalah terus memelihara permusuhan dan sibuk mencari kesalahan lawan. Jika ini yang terpelihara, maka energi bangsa akan banyak terbuang sia-sia.
Anies berhasil mengalahkan Ahok adalah fakta. Saat ini Anies sudah dilantik dan jadi gubernur Jakarta. Sejak dilantik Anies adalah gubernur seluruh rakyat Jakarta, bukan gubernurnya para pendukung, apalagi timses. Ini suatu keputusan yang sudah ditakdirkan undang-undang. Sepahit apapun, semua pihak mesti terima. Menyimpan rasa kecewa dan marah tidak akan merubah keputusan politik yang ada. Kecuali hanya akan buang energi. "The past can not be changed" kata Mary Pick Ford. Lebih produktif jika semua energi difokuskan bersama Anies-Sandi untuk membangun kota Jakarta dan bersama-sama menyelesaikan problem Jakarta.
Aksi yang hampir sama juga terjadi sebelumnya saat Anies Baswedan hadir di acara mantu Presiden Jokowi di Solo. Kehadiran Anies disambut oleh sejumlah tamu undangan dengan ucapan "huuuuu". Suara dilontarkan sebagai pesan bahwa mereka belum bisa terima Anies menjadi gubernur DKI. Sikap semacam ini menunjukkan bahwa kita masih harus lebih serius untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi yang lebih ilegan. Acara pesta agung Presiden Jokowi harus menanggung aib atas ulah segelintir tamu undangan yang terjangkit virus "prolonged infantilism". Kata anak muda, mereka masih belum bisa "move on."
Seorang pemimpin memang harus diuji, termasuk Anies. Peristiwa di atas menjadi ujian bagi Anies sejauh mana ia punya kematangan mental dan kedewasaan bersikap dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang perkembangannya tidak sepenuhnya bisa diduga. Apa jawaban dan reaksi Anies atas "perlakuan kurang terhormat" akan menjadi halaman pertama dimana masyarakat Jakarta siap menuliskan penilaiannya terhadap Anies.
Di satu sisi, sikap mereka memang layak dianggap telah menodai nilai-nilai demokrasi dan pantas mendapat kecaman publik sebagai "social punishment". Namun di sisi lain, ini justru menjadi bonus politik bagi Anies untuk menunjukkan siapa dirinya.
Menanggapi "suara nyinyir" di pesta mantu presiden Anies terlihat hanya tersenyum. Seolah tidak ada beban di wajahnya, meski telah ditertawakan. Reaksi senyum ini menjadi point penting, sebab ini memberi kesan betapa Anies oleh publik akan dinilai sebagai pemimpin yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Sikap "dewasa" yang ditunjukkan Anies kelak akan dimengerti sebagai investasi politik yang ilegan. Reaksi Anies ini membuktikan kelasnya sebagai pemimpin yang punya karakter. Pemimpin adalah sosok "eksepsional aktor" atau manusia di atas rata-rata (ordinary people). Karena itu seorang pemimpin dituntut punya karakter yang kuat. Menurut Napolion Bonaparte, tujuh puluh lima persen pengaruh seorang pemimpin ada di karakternya.
Jawaban Anies bahwa aksi walk out sejumlah orang di acara ulang tahun ke 90 Kolese Kanisius adalah hal biasa. Anies menegaskan bahwa tugasnya sebagai gubernur adalah menyapa dan mengayomi semua. Ini jawaban yang menunjukan kelasnya Anies sebagai negarawan, sekaligus menjadi garis tegas yang membedakan dirinya dari gubernur sebelumnya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Dilema Gatot Diantara Jokowi dan Habib Rizieq
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0